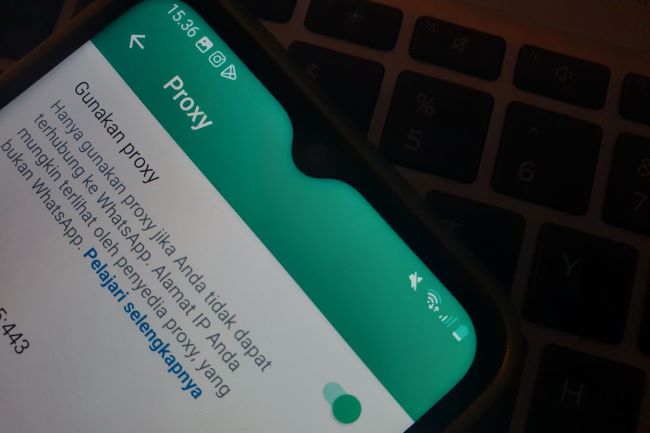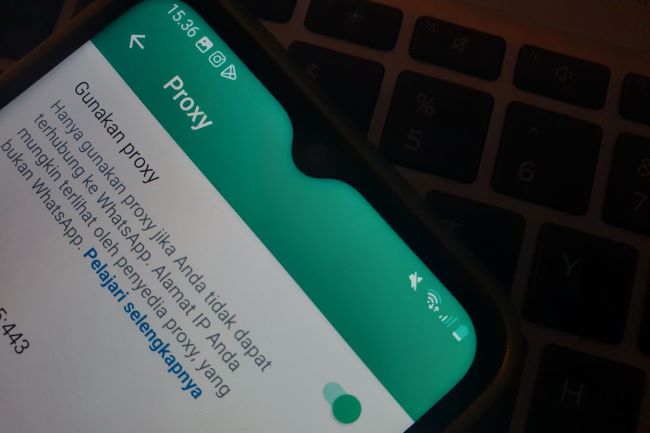Tahun 2019, pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres). Proses politik nasional yang terjadi menjelang Pilpres telah mengesankan adanya doel heillgt de middelen, yakni tujuan menghalalkan cara, untuk memenangkan pertarungan: antar elite-politik, terutama antar calon presiden. Pada praktiknya, melebihi etika the end justified the mean yang digagas seorang tokoh negarawan kontroversial dari zaman Renaissance, Niccolo Machiavelli (1469-1527). Dalam bukunya Il Principe (The Prince, Sang Penguasa), buku yang sering dikutip daripada dibaca. Keseringannya dikutip menunjukkan betapa pentingnya buku tersebut.
Arti pentingnya adalah karena Machiavelli membagi dunia dalam arti apa pun ke dalam dua kubu. Dibaginya dunia moral ke dalam dua kubu yang hampir tidak terjembatani, yakni dunia politik dan ahli ilmu politik. Dengan demikian, Machiavelli membagi publik pembaca, publik politik, publik moral ke dalam dua kubu yang mencintai dan membencinya. Tragedi buku Machiavelli melebihi karya-karya lain, karena Machiavelli dibenci justru oleh orang yang sangat mencintainya, yakni oleh para politisi yang memulai karirnya dengan menyumpah-serapahi Machiavelli, untuk kemudian mempraktikkan setiap ‘’kata’’ tanpa menghilangkan satu ‘’titik’’ pun. (Daniel Dhakidae, 1987).
Dalam Il Principe, Machiavelli mengembangkan teknik-teknik untuk merebut dan memantapkan pegangan atas kekuasaan politik. Demi tujuan itu, sang penguasa jangan mau dihambat oleh norma-norma moral. Penguasa harus bersikap kejam, tidak takut bohong, bersedia membunuh, jangan merasa terikat pada janji atau ikatan hutang budi. Seorang penguasa yang bermurah hati atau baik hati tidak akan berdaya. Kesediaan untuk mempertahankan kekuasaan dengan sarana apapun yang efetif, termasuk yang tidak bermoral, adalah inti paham yang disebut Machiavellisme.
Mengamankan Kekuasaan
Pendapat Machiavelli itu lahir atas hasil renungannya. Saat merenung, Machiavelli bertanya-tanya, mengapa penguasa bisa runtuh? Semakin mencari jawabnya, kian penasaranlah Machiavelli. Begitulah, Machiavelli menemukan jawabannya, bahwa negara akan aman dan bertahan lama, bila penguasa kuat. Untuk itu, penguasa tidak cukup hanya berwatak pemberani, gagah perkasa, apalagi hanya mengandalkan nasib mujur. Penguasa harus penuh perhitungan dan lihai menggunakan segala cara dan kesempatan.
Menurut Machiavelli, tujuan utama berpolitik bagi penguasa adalah mengamankan kekuasaan yang ada pada tangannya. Baginya, politik dan moralitas merupakan dua bidang yang terpisah, dan tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain.
Dalam urusan politik, tidak ada tempat membicarakan masalah moral. Hanya satu hal yang penting, ialah bagaimana meraih kesuksesan dengan memegang kekuasaan. Norma etika politik alternatif bagi Machiavelli, tujuan berpolitik adalah memperkuat dan memperluas kekuasaan. (M. Sastrapratedja dan Frans M. Parera, 2001).
Banyak penguasa yang salah kaprah dalam memahami karya Machiavelli. Pemuja teori Machiavelli telah lahir dari masa ke masa. Dikatator Italia, Mussolini; atau mantan penguasa Jerman, Adolf Hitler; juga Lenin, Stalin dari Rusia, termasuk dalam deretan pemuja teori itu. Termasuk juga Ferdinand Marcos dari Filipina; Ketua Mao dari Cina; Pol Pot dari Kamboja; Pinochet dari Chili; atau para mantan penguasa rezim apartheid Afrika Selatan menerapkan teori itu dengan bersemangat, tekun dan konsisten.
Buku Il Principe yang banyak dipegang oleh para diktator untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menghalalkan segala cara. Apakah itu dengan teror, dekrit, maklumat, pengerahan massa, penciptaan keadaan darurat, pemerintahan tangan besi, dan lain-lain. Yang penting kekuasaan tetap beada di tangan, apa pun akbatnya bagi bangsa dan negara.
Membuat Takut Masyarakat
Menurut Franz Magnis-Suseno, kebrutalan Machiavelli menomorsatukan raison d’etat – negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk mempertahankan diri tanpa perhatian terhadap hukum dan moralitas – sekaligus mengejutkan dan mempesona para filosof dan politilog. Namun pesona itu jangan sampai membuat kita buta terhadap beberapa defisit serius, kalau tidak fatal, dalam konsepsi Machiavelli. (Franz Magnis-Suseno, 1997).
Tiga defisit yang paling gawat adalah: pertama, dengan fokus seluruh perhatian pada kemampuan penguasa untuk membuat takut masyarakat (‘’biar mereka benci, asal takut’’), maka syarat paling dasar stabilitas kekuasaannya – seperti dianalisis oleh filsuf Hannah Arendt dan Max Weber – telah luput sama sekali dari perhatiannya. Kekuasaan yang sebenarnya tidak berdasarkan rasa takut, melainkan berdasarkan pengakuan masyarakat terhadap penguasa. Dengan mengikuti resep Machiavelli justru tidak menghasilkan kemantapan.
Kedua, kalau pun kekerasan, penipuan, kekejaman, dan pembunuhan hanya dipakai untuk merebut kekuasaan pada permulaannya, namun dengan demikian penguasa memberi isyarat yang fatal. Bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya, akan memakai segala cara. Segala konflik politik otomatis harus memakai cara-cara itu juga. Dengan membuang moralitas sebagai kriteria kewajaran sarana konflik. Machiavelli justru mengabadikan cara berpolitik gaya condotieri (kepala pasukan liar) yang mau diatasinya itu. Kepentingan nasional memang harus dinomorsatukan, tetapi apabila hal itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis dan tidak manusiawi, justru mentorpedo diri sendiri: kepentingan dasar nasional adalah perwujudan kehidupan bersama yang adil dan manusiawi.
Yang ketiga, Machiavelli mereduksikan seni berpolitik pada rekayasa kekuasaan. Bahwa yang menentukan bagi kemantapan sistem politik adalah struktur dan institusi-institusi, terutama pelembagaan kontrol dan mekanisme korektif, ini pun luput total terhadap perhatiannya. Padahal justru dalam masyarakat pasca-tradisional (yang begitu jeli diantisipasi oleh Machiavelli) hilangnya kerangka acuan tradisi perlu diimbangi oleh struktur yang mengimbangi perangai mental pribadi penguasa.
Etika Politik
Di negeri tercinta ini, teori Machiavelli dalam bentuknya yang lain, juga hadir dengan ‘’gagah’’nya. Contoh yang paling konkret adalah dalam konteks perpolitikan bangsa Indonesia saat ini. Pertanyaan secara filosofis yang perlu diajukan adalah, apakah benar partai politik di Indonesia sekarang ini benar-benar berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia dan nasib rakyat Indonesia? Hal inilah sejatinya yang perlu dijawab oleh elite partai politik dan para calon pemimpin ke depan demi kemajuan bangsa Indonesia.
Menurut Syahrul Kirom, peneliti dari UGM Yogyakarta, bahwa fakta di lapangan menunjukkan bangsa Indonesia sekarang ini mengalami kebangkrutan politik. Politik di Indonesia bukan lagi ditujukan untuk semangat memperjuangkan nasib seluruh rakyat Indonesia, atau untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Melainkan, politik di Indonesia lebih menekankan pada individu, dan bagaimana cara mengeruk anggaran negara melalui akses kekuasaan dan elite politik di DPR, dan lebih memperjuangkan partai politiknya masing-masing dalam mengegolkan hasrat kekuasaannya. (Syahrul Kirom, 2017).
Etika politik di Indonesia kian Machiavellian, menghalalkan segala cara, tidak mengerti mana yang halal dan haram. Penyakit korupsi yang dilakukan oleh elite politik hampir terjadi di seluruh partai politik yang ada. Partai politik tidak ada yang bersih dari penyakit korupsi. Semua partai politik di Indonesia saat ini menunjukkan demokrasi yang keblinger atau kebablasan. Karena para elite politik tidak mengerti betul sejarah kebangkitan nasional yang telah melahirkan suatu partai politik di Indonesia dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan dan nasib hak hak warga negara Indonesia.
Senyatanya, elite politik dan kepala daerah banyak yang terlibat korupsi dan praktik pencucian uang. Hal ini menunjukkan pada bangsa Indonesia, bahwa perpolitikan di Indonesia mengalami kebangkrutan dalam menalar secara politik. Elite politik ternyata tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai etika politik, politik kebangsaan, politik kemanusiaan, dan politik kejujuran.
Penulis : Soetanto Soepiadhy Dosen UNTAG Surabaya dan Pendiri ‘’Rumah Dedikasi’’ Soetanto Soepiadhy

Redaksi yang malang melintang di bidang jurnalisme