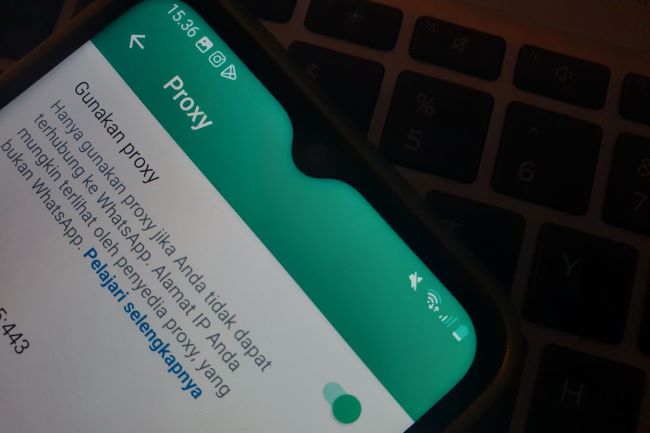Ibadah haji secara syari hukumnya wajib. Tetapi hukum wajibnya tidak bersifat mutlak karena hanya ditujukan kepada mereka yang telah mampu. Dilihat dari ilmu ekonomi, ibadah haji adalah kebutuhan bagi mereka yang telah mampu dan karenanya harus dipenuhi. Bagi mereka, pemenuhan kebutuhan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya karena mereka memang memiliki rezeki yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Oleh karena itu sangat jelas dinyatakan bahwa ibadah haji adalah wajib bagi orang-orang yang telah mampu sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran : 97, yang artinya : ‘’Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah’’.
Namun demikian, kewajiban menunaikan ibadah haji hanyalah sekali dalam seumur hidup sebagaimana hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam : ‘’Wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian ibadah haji maka tunaikanlah haji kalian!’’ Seseorang berkata: ‘’Apakah setiap tahun, ya Rasulullah?’’ Beliau terdiam sehingga orang tersebut mengulangi ucapannya tiga kali. Lalu Rasulullah bersabda: ‘’Kalau aku katakan ya, niscaya akan wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup’’. (HR. Ahmad, Muslim dan Nasai)
Sedangkan bagi mereka yang belum mampu, ibadah haji hanyalah keinginan sehingga tidak wajib dipenuhi. Artinya dari pada mereka direpotkan oleh keinginan beribadah haji dengan bersusah payah memaksakan diri menabung hingga mengabaikan kewajiban yang sudah ada di depan mata, yakni memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan bagi diri sendiri dan segenap anggota keluarganya, mereka lebih baik dan wajib hukumnya menyibukkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut sebagai kewajiban syari dan sosial.
Jika kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi, mereka bisa meningkatkan status keinginan beribadah haji menjadi azam atau keinginan kuat. Mereka yang telah memiliki keinginan kuat untuk beribadah haji, tentu akan terdorong untuk menabung sebagian penghasilannya agar bisa menunaikan ibadah haji. Ketika tabungan telah mencapai sejumlah tertentu yang setara dengan ongkos naik haji (ONH) dan biaya-biaya lainnya, maka keinginan kuat tersebut meningkat menjadi kebutuhan. Pada tingkat ini menjadi wajib menunaikan ibadah haji dan karenanya harus dipenuhi.
Pengetahuan tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan menurut ilmu ekonomi sebagaimana diuraikan di atas adalah penting sebab dengan pemahaman yang benar kita bisa bersikap bijak dalam memahami rukun Islam kelima tersebut. Jangan sampai terjadi kita memaksakan diri mengejar ibadah haji padahal sebetulnya belum wajib hukumnya karena belum mampu. Ibarat shalat, waktunya belum masuk tetapi sudah melakukannya. Shalat seperti ini sudah pasti tidak sah. Sedangkan haji seperti ini bermasalah setidaknya secara akhlak karena mengabaikan kewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar keluarga. Bukankah sangat ironis apabila orang tua berangkat ibadah haji, sementara anak-anaknya dibiarkan tidak bersekolah dan kesehatannya memburuk tidak ditangani secara serius karena alasan biaya.
Ibadah haji seperti itu secara hukum agama sulit dibenarkan. Di dalam ilmu agama juga dikenal konsep fiqh al-aulawiyyat atau fiqih prioritas sebagaimana digagas oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dari Mesir. Dijelaskan dalam pengantar kitabnya berjudul ‘’Fi FiqhilAulawiyyat’’, halaman 9, tentang maksud fiqih prioritas, yang artinya: ‘’Yang dimaksud dengan fiqh prioritas adalah meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan dalil, dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang mula-mula dikerjakan harus didahulukan berdasarkan penilaian syariah yang shahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal’’.
Jadi, fiqih prioritas pada intinya adalah menekankan urutan pelaksanaan kewajiban atau beban sesuai dengan tingkatan hukumnya. Berdasarkan pada prinsip ini sesuatu yang hukumnya fardhu ain harus diutamakan dari pada sesuatu yang hukumnya fardhu kifayah. Sesuatu yang hukumnya wajib harus didahulukan dari pada sesuatu yang hukumnya sunnah. Sesuatu yang manfaatnya besar dan luas harus didahulukan dari pada sesuatu yang manfaatnya kecil dan terbatas, dan seterusnya.
Syekh Dr. Yusuf Al-Qardhawi memberikan contoh dalam masalah ini bahwa ibadah haji bagi orang-orang yang telah melaksanakannya tidak wajib melaksanakan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Bagi mereka ibadah haji berikutnya sudah turun tingkatan hukumnya, yakni tidak wajib. Bagi orang-orang seperti itu juga berlaku fiqih prioritas dimana mereka harus lebih mengutamakan ibadah lain yang hukumnya wajib dari pada melakukan ibadah haji atau umroh kesekian kali yang hukumnya hanya sunnah.
Dalam kaitan itu, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengkritik orang-orang kaya yang sering melakukan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci, tetapi pada saat yang sama mereka abai terhadap fakta bahwa di masyarakat masih banyak orang miskin Muslim. Tidak sedikit dari mereka berpindah agama karena tidak mendapatkan pertolongan dari saudara-saudara Muslim yang kaya. Orang-orang kaya itu sebetulnya wajib hukumnya berjihad di jalan Allah dengan menggunakan hartanya untuk mencegah pemurtadan di antara orang-orang miskin Muslim tersebut, misalnya dengan memberikan beasiswa untuk bersekolah, mengikuti kursus ketrampilan atau menyediakan modal yang cukup untuk bekerja.
Di sisi lain, kita melihat baberapa orang dari kalangan ekonomi lemah melaksanakan ibadah haji dengan sebelumnya menabung selama bertahun-tahun. Hal ini tentu tidak menjadi masalah dan bahkan baik selama dalam menabung itu mereka tidak mengabaikan kewajibannya.
Namun, jika kegiatan menabung untuk ibadah haji ternyata menjadikan anak-anak tidak mendapatkan haknya untuk memperolah pendidikan yang cukup dan kesehatan yang memadai, hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip fiqih prioritas. Bagaimanapun mencari ilmu hukmunya wajib, dan orang tua wajib hukumnya mengusahakan biaya sekolah bagi anak-anaknya, disamping kewajiban lain yakni menafkahi dan mengobatkan mereka yang sakit.
Dalam kondisi seperti itu ibadah haji tidak wajib bagi mereka dari kalangan ekonomi lemah, karena ibadah haji memang hanya diwajibkan bagi yang telah mampu. Mereka tetap mendapat pahala dari keinginan atau niatnya menunaikan ibadah haji tersebut. Hal ini berdasarkan hadits Rasululullah shallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi : ‘’Niat seorang mukmin lebih utama dari pada amalnya’’.
Hadits lain yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim berbunyi : ‘’Maka barang siapa memiliki keinginan atau berniat melakukan sesuatu kebaikan lalu tidak jadi melaksanakannya, Allah akan mencatat pahalanya di sisi-Nya satu kebaikan sempurna’’.
Sekali lagi, ibadah haji wajib hukumnya. Namun demikian Allah tidak bermaksud membebani hamba-hamba-Nya dengan mewajibkan rukun Islam kelima itu kecuali sebatas kemampuan masing-masing. Allah berfirman-Nya dalam QS. Al-Baqarah : 286, yang artinya ‘’Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya’’. Hal senada juga ditegaskan dalam QS. Al Maidah : 6, ‘’Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian’’.
Kedua ayat tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi kaum Muslimin dalam menyikapi kewajiban-kewajiban agama sebagaimana dirumuskan dalam Rukun Islam, khususnya kewajiban beribadah haji ke Tanah Suci di Makkah al-Mukarramah, Saudi Arabia, yang memang membutuhkan biaya yang sangat banyak dan kemampaun fisik yang tidak bisa dianggap enteng. ibadah haji memang tidak terlepas dari kedua hal ini.
Sumber : https://islam.nu.or.id
Reporter : MKM
Editor : LA_Unda