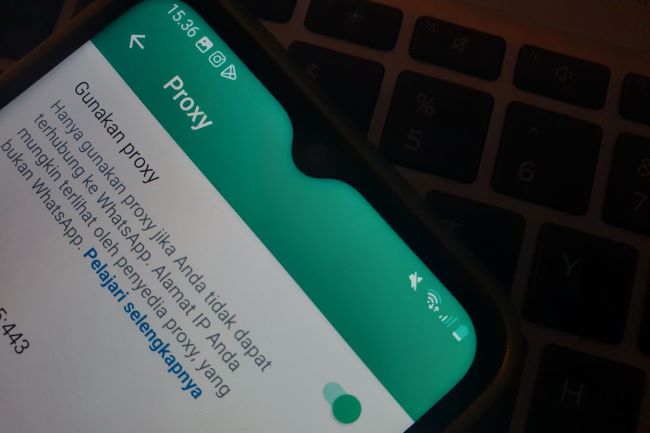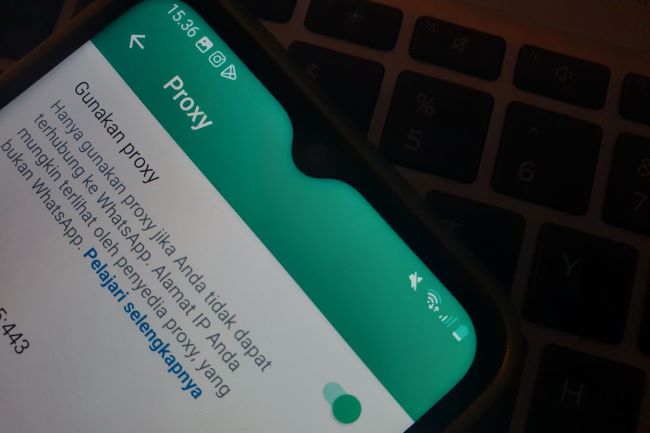Markeso, si pengamen ludruk garingan atau ontang-anting, merupakan pelawak kesayangan rakyat kebanyakan di sudut-sudut kota di Jawa Timur. Begitulah Cak Madi ‘’melakonkan’’ tokoh Markeso dalam acara Bengkel Sastra #3 ‘’perempuan bicara perempuan’’, 18 April 2018 di Selasar Gedung Utama Balai Pemuda Surabaya.
Sebelum acara Cak Madi, didahului orasi budaya oleh Sirikit Syah, Vika Wisnu, dan Maya A. Zahra.
Ketiganya berbicara tentang persoalan kiprah perempuan di sektor publik. Hal ini dimungkinan, karena permasalahan perempuan dalam lintasan sejarah merupakan permasalahan sosial yang belum berimbang dalam memandang kaum perempuan. Dalam masyarakat yang mengaku modern dan demokratis sekalipun, masih dijumpai pandangan yang menganggap, bahwa perempuan merupakan ‘’supplement’’, sehingga kiprahnya di sektor publik layak dipertanyakan.
Kegoncangan Moral
Begitu Cak Madi tampil, saya jadi teringat novel Ibu Kita Raminten, karya Muhammad Ali (Sinar Harapan, 1982), sastrawan yang pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Surabaya, sekitar tahun 80-an. Markeso, sebagai pengamen ludruk garingan, dengan penghasilan pas-pasan, ia hidup bersama Raminten isterinya, di sebuah gubug di pinggiran kota.
Sebagai rakyat ‘’kecil’’ yang tak punya kelebihan penghasilan, Markeso dan Raminten jarang menikmati hiburan di luar rumah. Ini yang menjadi sebab, bahwa satu-satunya hiburan yang mengasyikkan adalah menutup pintu gubug-nya setiap pukul sembilan malam. Boleh jadi, itulah sebab-musababnya, mengapa Raminten melahirkan anak setiap tahunnya.
Bayi-bayi yang dilahirkan oleh Raminten semuanya dijual, bahkan ada yang sudah ditawarkan, ketika masih di dalam kandungan. Anak-anaknya yang diberikan kepada orang lain itu kesemuanya berjumlah dua belas orang. Dan di tangan orang lain, anak-anak itu akhirnya menjadi orang baik-baik dan berpangkat. Raminten masih ingat semua nama anak-anaknya dan kepada siapa dijualnya, karena Raminten dan Markeso minta kepada mereka yang membeli untuk tidak mengganti nama-nama anaknya.
Stambul, anak yang ke tiga belas dan terakhir, benar-benar seorang anak yang memprihatinkan. Anak itu tidak diberikan kepada orang lain, dipelihara oleh Raminten dan Markeso sendiri. Dari kecil Stambul tumbuh menjadi anak nakal, memperlihatkan semangat merusak, menghancurkan apa saja yang dilihatnya. Setelah tumbuh menjadi dewasa, ia menjadi pencuri, tukang berkelahi, bahkan menjadi perampok.
Markeso meninggal dunia. Raminten menjadi sangat repot terhadap perbuatan-perbuatan Stambul. Sangat keterlaluan, tak bermoral, ia memaksa menjual Raminten, ibu kandungnya sendiri, kepada Babah Wong, seorang Cina tua. Karena hinaan dan naluri kebangsaan yang timbul, akhirnya Stambul membunuh Babah Wong. Dan dari Stambul itulah, Raminten dapat bertemu dengan ke dua belas anak-anaknya di ruang sidang pengadilan.
Raminten, Pribadi yang Lepas dari Masyarakat
Tentang kesempurnaan biologis Raminten. Muhammad Ali mengungkapkan sebagai berikut:
Raminten tampak sehat dan menggairahkan. Kedua teteknya tetap atos dan ujungnya yang lancip menonjol tajam di balik bajunya. Lesung pipit pada pipinya yang kentara apabila ia tersenyum, tahi lalat kecil di bawah dagunya menambah kesemarakan kecantikannya yang alamiah. Kulitnya lembut, resik dan mulus. Bentuk kakinya indah, dan rambutnya hitam ikal dan andan-andan (h. 49).
Namun, di balik keindahan tubuh itu, bagaimana diri pribadi isteri Markeso? Dengan lugas Muhammad Ali menelanjanginya, sama sekali tanpa ke-rikuh-an. Muhammad Ali tak rikuh pada kewajiban moral insan budayawan yang kini diwajibkan keadaan untuk terlibat dalam semangat pengibaran panji pembangunan dewasa ini.
Muhammad Ali menerobos pola-pola sosial yang kini terpancang di mana-mana. Ia masih konsisten pada realitas, betapa pun langka realitas yang diangkatnya. Masih banyak perempuan-perempuan lapisan bawah yang suka menghabiskan waktunya dengan didis, sementara produk-produk teknologi dan industri begitu datang membanjiri desa dan pusat-pusat kediaman kaum urban?
Kita bisa menjadi curiga, atas kecenderungan Muhammad Ali mendramatisasi lingkup lapisan sosial terbawah ini. Sebab secara jelas digambarkan, bahwa tempat tinggal suami-isteri Markeso terletak di pinggiran kota besar, dan bukan di lereng gunung atau di pedalaman Kalimantan yang sukar disentuh modernisasi sosial.
Kecurigaan itu menjadi-jadi setelah mengikuti bagian lain dari tulisan Muhammad Ali, antara lain: Ketika itu Markeso sedang berbaring telentang di sebelah isterinya yang hanya mengenakan jarik tanpa berkutang (h. 19-20). Apalagi ketika Muhammad Ali dengan terang-terangan memaparkan situasi batin Raminten yang betul-betul buta terhadap Tuhan serta kekuasaan-Nya (h. 43-44).
Bisakah diterima dengan akal yang paling sederhana sekalipun, bahwa Raminten yang setia, yang tak suka rasan-rasan tetangga itu sama sekali tak pernah mengenal Allah, Tuhan? Ya, sampai-sampai Raminten harus meminta suaminya untuk menerangkan perihal kekuasaan Allah pada suaminya: “Ah, cobalah terangkan, supaya saya dapat mengerti” (h. 44).
Raminten di Bawah Bayang-bayang Masyarakatnya
Di dalam masyarakat selalu ada dan dimungkinkan adanya double reality, yaitu di satu pihak ada sistem fakta (yang tersusun atas segala apa yang senyatanya di dalam kenyataan ada), dan di lain pihak ada sistem normatif (sistem yang berada di dalam mental yang membayangkan segala apa yang seharusnya ada).
Apa yang dibayangkan di dalam mental sebagai suatu keharusan itu, sesungguhnya adalah selalu sesuatu yang di dalam kenyataan merupakan sesuatu yang betul-betul ada, dan/atau yang mungkin ada. Norma, atau keharusan, selalulah mempertimbangkan alam kenyataan dan mempertimbangkan pula segala kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam situasi fakta (Soetandyo Wignjosoebroto, 1975:5-6).
Baik Raminten maupun Markeso adalah pasangan yang meski miskin batin dan material, namun setia pada lingkaran double reality di luar kehendak maupun kesadarannya. Mereka tak sembarangan memberi nama anak-anaknya. Mereka selektif dalam menentukan siapa orang-orang yang bisa diserahi anaknya. Pemilihan atas keluarga-keluarga yang dianggapnya ‘’pantas’’ dan ‘’bisa’’ memelihara dan membesarkan anak-anak mereka adalah tumpuan harapan agar anak-anak tersebut nantinya jadi orang.
Secara sosiologis, perilaku atau proses jiwa, baik Markeso maupun Raminten isterinya berada dalam satu tata determinan, di mana pemenuhan hajat hidup secara normal bagi anak-anaknya akan terjamin. Itu semuanya adalah fragmentasi abstraktif dalam kalbu mereka. Yang didukung kenyataan menurut apa yang berhasil diamati dan direkam batin Markeso dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada orang-orang yang tergolong mampu itu, tempat mereka menumpuk harapan-harapan bagi sang anak. Jadi abstraksi yang berkembang dalam hati mereka dilandasi oleh fakta yang nyata-nyata mereka saksikan.
Perbuatan di Luar Norma
Pengangkatan anak, menurut norma hukum harus dilaksanakan menurut prosedur yuridis, tak pernah tegas ditulis oleh Muhammad Ali. Mungkin kurang memahami masalah-masalah yuridis ataukah sekedar ingin memberi latar belakang lebih tegas atas kehidupan suami-isteri Markeso, sukar diamati dalam novel ini.
Sosiologi hukum hanya secara samar bisa meraba permukaan novel ini. Tapi tidak sampai menyentuh hakiki masalahnya. Markeso maupun Raminten tak punya komunikasi akrab dengan masyarakatnya. Padahal lapisan bawah, biasanya amat intim dalam pergaulan. Jawaban dari masalah di atas, ternyata terletak pada diri Markeso maupun Raminten.
Markeso maupun Raminten menyadari, bahwa mereka telah berbuat sesuatu yang menyimpang dari norma. Maka segera terasa olehnya, bahwa mereka telah menempatkan dirinya di luar masyarakatnya. Oleh sebab itu mereka merasa, bahwa kekuatan masyarakat tidaklah lagi berada di belakang mereka, melainkan justru berhadap-hadapan serta menantangnya. Inilah sebabnya kehidupan mereka semakin terbelenggu oleh kekerdilan. Terutama Raminten yang setiap detik berada dalam lingkaran masyarakatnya.
Agaknya Muhammad Ali lebih tegas memberi warna beda antara keluarga pengamen ini dengan sosio kultur yang hidup. Di mana ketika Markeso sakit sampai meninggal dunia, begitu simpatik uluran tangan masyarakat menggapai Raminten. Namun pada akhirnya, Raminten harus tersentak dalam kedukaannya, ketika Stambul menyentiknya ke kancah kekerasan yang memperkosa norma dan kemanusiaan.
Penulis : Soetanto Soepiadhy Dosen Untag Surabaya, dan Pendiri ‘’Rumah Dedikasi’’ Soetanto Soepiadhy

Redaksi yang malang melintang di bidang jurnalisme